Syech Ibrahim bin Adham RA.
Beliau adalah seorang ulama yang lahir di Balkh dari keluarga bangsawan Arab.
Dalam sejarah sufi, Beliau disebutkan sebagai seorang penguasa yang meninggalkan kerajaannya, lalu mengembara ke arah Barat untuk menjalani hidup bersendirian yang sempurna sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang halal hingga Beliau meninggal dunia di negeri Persia kira-kira tahun 165H/782M.
Beberapa sumber mengatakan bahwa Beliau terbunuh ketika mengikuti angkatan laut yang menyerang Bizantium.
Kisah taubatnya merupakan sebuah kisah yang unik dalam kehidupan kaum muslimin.
Syahdan, awalnya Ibrahim bin Adham adalah seorang penguasa di Balkh dan memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas.
Kemanapun beliau pergi, empat puluh buah pedang emas dan empat puluh buah tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya.
Pada suatu malam ketika ia tertidur di bilik istananya, atas bilik itu berderak-derik seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap.
Beliau terjaga dan berseru
“Siapakah itu?”
“Sahabatmu. Untaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap ini” terdengar sebuah sahutan.
“Bodoh, engkau handak mencari unta di atas atap?” seru Ibrahim.
“Wahai manusia yang lalai” suara itu menjawab.
“Apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutra dan tidur di atas katil emas?” suara itu menjawab.
Kata-kata itu sangat mengecutkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah dan tidak dapat meneruskan tidurnya.
Ketika hari telah siang, Ibrahim pergi ke ruang tamu dan duduk di atas singgasananya sambil berfikir, risau dan merasa amat bimbang.
Para menteri berdiri di tempat masing-masing dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka.
Kemudian dimulailah pertemuan terbuka.
Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruang tamu itu. Wajahnya begitu menyeramkan sehingga tidak seorang pun di antara anggota-anggota maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya. Semua lidah menjadi kelu. Dengan tenang lelaki tersebut melangkah ke depan singgasana.
“Apakah yang engkau inginkan?” tanya Ibrahim.
“Aku baru saja sampai ke tempat persinggahan ini” jawab lelaki itu.
“Ini bukan tempat persinggahan para kafilah. Ini adalah istanaku. Engkau sudah gila!” Ibrahim menghardiknya.
“Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?” tanya lelaki itu.
“Ayahku” jawab Ibrahim.
“Dan sebelum ayahmu?”
“Kakekku”
“Dan sebelum kakekmu?”
“Ayah dari kakekku”
“Dan sebelum dia?”
“Kakek dari kakekku”
“Ke manakah mereka sekarang ini?” tanya lelaki itu.
“Mereka telah tiada. Mereka telah mati” jawab Ibrahim.
“Jika demikian, bukankah ini tempat persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya?”
Setelah berkata demikian lelaki itu hilang. Sungguh ada yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir AS.
Sejak hari itu, kegelisahan dan kerisauan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi.
Ia dihantui oleh bayang-bayangnya sendiri dan terdengar suara-suara di malam hari, kedua-duanya sama merisaukan.
Akhirnya, karena tidak tahan lagi, pada suatu hari Ibrahim berkata.
“Siapkan kudaku! Aku hendak pergi berburu. Aku tidak tahu apakah yang telah terjadi terhadap diriku sejak belakangan ini. Ya Allah, bilakah semua ini akan berakhir?”
Setelah kudanya disiapkan lalu ia berangkat pergi memburu. Kuda itu dipacunya melalui padang pasir, seolah-olah ia tidak sadar akan segala perbuatannya.
Dalam kerisauan itu ia terpisah dari rombongannya.
Tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan.
“Bangunlah!”
Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu. Ia terus memacu kudanya. Untuk kali keduanya suara itu berseru kepadanya, namun Ibrahim tetap tidak mempedulikannya.
Ketika suara itu berseru untuk kali ketiganya, Ibrahim semakin memacu kudanya.
Akhirnya untuk kali keempat, suara itu berseru “Bangunlah sebelum engkau kupukul!”
Ibrahim tidak dapat mengendalikan dirinya. Di saat itu terlihat olehnya seekor rusa. Ibrahim hendak memburu rusa itu tetapi tiba-tiba binatang itu berkata kepadanya “Aku disuruh untuk memburumu. Engkau tidak dapat menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan atau inikah yang diperintahkan kepadamu?”
“Tuhan, apakah yang menghalang diriku ini?” seru Ibrahim.
Ia memalingkan wajahnya dari rusa tersebut. Tetapi dari tali pelana kudanya terdengar suara yang menyerukan kata-kata yang serupa, Ibrahim kebingungan dan ketakutan.
Seruan itu semakin jelas, karena Allah Yang Maha Berkuasa mau menunaikan janji-Nya. Kemudian suara yang serupa berseru lagi dari bajunya.
Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim.
Keyakinan yang teguh telah tertanam di dalam dadanya.
Ibrahim turun dari tunggangannya.
Seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air matanya.
Dengan sepenuh hati Ibrahim bertaubat kepada Allah.
Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seorang gembala yang memakai pakaian dan topi dibuat dari bulu kambing biri-biri.
Pengembala itu sedang menggembalakan sekumpulan binatang.
Setelah diamatinya, ternyata si pengembala itu adalah hambanya yang sedang menggembalakan biri-biri kepunyaannya. Kepada pengembala itu Ibrahim menyerahkan pakaian yang bersulam emas, topinya yang bertatahkan batu permata, sedang dari pengembala itu Ibrahim meminta pakaian dan topi dari bulu biri-biri yang sedang dipakainya.
Ibrahim lalu memakai pakaian dan topi bulu milik pengembala itu dan semua malaikat menyaksikan perbuatannya itu dengan penuh kekaguman.
“Betapa megah kerajaan yang diterima putera Adam ini” malaikat-malaikat itu berkata.
“Ia telah mencampakkan pakaian keduniaan yang kotor, lalu menggantikannya dengan jubah kepapaan yang megah”
Dengan berjalan kaki, Ibrahim bermusafir melalui gunung-ganang dan padang pasir yang luas sambil menyesali segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya.
Akhirnya ia sampai di Merv.
Di sini Ibrahim melihat seorang lelaki terjatuh dari sebuah jambatan.
Pasti ia akan mati dihanyutkan oleh air sungai.
Dari jauh Ibrahim berseru “Ya Allah, selamatkanlah dia!”
Seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di awang-awang, sehingga orang lain tiba dan menariknya ke atas.
Dan dengan merasa heran mereka memandang Ibrahim.
“Manusia apakah itu?” seru mereka.
Ibrahim meninggalkan tempat itu dan terus berjalan sampai ke Nishapur.
Di kota Nishapur, Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil di mana ia dapat tekun mengabdikan diri kepada Allah.
Akhirnya bertemulah ia dengan sebuah gua yang akan menjadi amat terkenal.
Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama sembilan tahun, tiga tahun pada setiap ruang yang terdapat di dalamnya. Tidak seorang pun yang tahu apakah yang telah dilakukannya baik siang maupun malam di dalam gua itu, karena hanya seorang manusia yang luar biasa gagahnya yang sanggup sendirian di dalam gua itu pada malam hari.
Setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mencari kayu api. Keesokan paginya ia pergi ke Nishapur untuk menjual kayu-kayu itu.
Setelah melakukan solat Jum'at, ia pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya diberikan kepada pengemis dan separuhnya lagi untuk membuka puasanya.
Demikianlah yang dilakukannya setiap minggu.
Pada suatu malam di musim salju, Ibrahim sedang berada di tempat ibadah.
Malam itu udara sangat dingin dan untuk bersuci Ibrahim harus memecahkan es. Sepanjang malam badannya menggigil, namun ia tetap mengerjakan sholat dan berdoa hingga fajar menyinsing.
Ia hampir mati kedinginan.
Tiba-tiba ia teringat pada api.
Di atas tanah dilihatnya ada sebuah kain bulu.
Dengan kain bulu itu sebagai selimut, ia pun tertidur.
Setelah hari terang benderang, barulah ia terjaga dan badannya terasa hangat.
Tetapi ia segera sadar bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu itu adalah seekor naga dengan biji mata berwarna merah darah.
Ibrahim berdoa “Ya Allah, Engkau telah mengirimkan mahkluk ini dalam bentuk yang halus, tetapi sekarang terlihatlah bentuk sebenarnya yang sangat mengerikan. Aku tidak kuat menyaksikannya”
Naga itu segera bergerak dan meninggalkan tempat itu setelah dua atau tiga kali bersujud di depan Ibrahim.
Ketika kemasyhuran kealimannya tersebar luas, Ibrahim meninggalkan gua tersebut dan pergi ke Makkah.
Di tengah perjalanan, Ibrahim berjumpa dengan tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya Nama Yang Teragung dari Allah, dan setelah itu pergi meninggalkannya.
Dengan Nama Yang Teragung itu Ibrahim menyeru Allah dan sesaat kemudiaan nampaklah olehnya Nabi Khidir as.
“Ibrahim” kata Nabi Khidir kepadanya. “Saudaraku Daud yang mengajarkan kepadamu Nama Yang Teragung itu”
Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah.
Dengan izin Allah, Nabi Khidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim.
perjalanannya menuju Makkah, Ibrahim menceritakan seperti ini
“Setibanya di Zatul Iraq, kudapati seramai tujuh puluh orang yang berjubah kain perca bergelimpangan mati dan darah mengalir dari hidung dan telinga mereka. Aku berjalan di sekitar mayat-mayat tersebut, ternyata salah seorang di antaranya masih hidup”
“Anak muda, apakah yang telah terjadi?” Aku bertanya kepadanya.
“Wahai anak adam” jawabnya padaku. “Duduklah berhampiran air dan tempat sholat, janganlah menjauhinya agar engkau tidak dihukum, tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka. Tidak seorang manusia pun bersikap terlampau berani di depan sultan. Takutilah Sahabat yang memukul dan memerangi para penziarah ke tanah suci seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani. Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berharap Allah dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah katapun di dalam perjalanan, tidak akan memikirkan apa pun kecuali Allah, sentiasa membayangkan Allah ketika berjalan maupun istirahat, dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali kepada-Nya”
Setelah kami mengarungi padang pasir dan sampai ke tempat di mana para penziarah harus mengenakan jubah putih, Khidir as datang menghampiri kami. Kami mengucapkan salam kepadanya dan Khidir membalas salam kami. Kami sangat gembira dan berkata “Alhamdulillah, sesungguhnya perjalanan kita telah diridhoi Allah, dan yang mencari telah mendapatkan yang dicari, karena bukankah orang soleh sendiri telah datang untuk menyambut kita”
Tetapi saat itu juga berserulah sebuah suara dalam diri kami “Kamu pendusta dan berpura-pura! Begitulah kata-kata dan janji kamu dahulu? Kamu lupa kepada-Ku dan memuliakan yang lain. Binasalah kamu! Aku tidak akan membuat perdamaian dengan kamu sebelum nyawa kamu Kucabut sebagai pembalasan dan sebelum darah kamu Kutumpahkan dengan pedang kemurkaan" Manusia-manusia yang engkau saksikan bergelimpangan di sini, semuanya adalah korban dari pembalasan itu.
Wahai Ibrahim, berhati-hatilah engkau! Engkau pun mempunyai cita-cita yang sama. Berhati-hatilah atau pergilah jauh-jauh dari situ?
Aku sangat takut mendengar kisah itu. Aku bertanya kepadanya “Tetapi mengapakah engkau tidak turut dibinasakan?”
Kepadaku dikatakan “Sahabat-sahabatmu telah matang, sedang engkau masih mentah. Biarlah engkau hidup sesaat lagi dan akan menjadi matang. Setelah matang engkau pun akan menyusul mereka”
Setelah berkata demikian ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Ibrahim pun tiba di Makkah
Empat belas tahun lamanya Ibrahim mengarungi padang pasir, dan selama itu pula ia selalu berdoa dan merendahkan diri kepada Allah.
Ketika hampir sampai ke kota Makkah, para sesepuh kota hendak menyambutnya. Ibrahim mendahului rombongannya agar tidak seorang pun dapat mengenali dirinya. Hamba-hamba yang mendahului para sesepuh tanah suci itu melihat Ibrahim, tetapi karena belum pernah bertemu dengannya, mereka tidak mengenalinya.
Setelah Ibrahim begitu dekat, para sesepuh itu berseru ”Ibrahim bin Adham hampir sampai. Para sesepuh tanah suci telah datang menyambutnya”
“Apakah kamu inginkan dari si bida'h itu?” tanya Ibrahim kepada mereka.
Mereka langsung menangkap Ibrahim dan memukulnya.
“Para sesepuh tanah suci sendiri datang menyambut Ibrahim tetapi engkau menyebutnya bid'ah?” hardik mereka.
“Ya, aku katakan bahwa dia adalah seorang bida'ah” Ibrahim mengulangi ucapannya.
Ketika mereka meninggalkan dirinya, Ibrahim berkata pada dirinya sendiri “Engkau pernah menginginkan agar para sesepuh itu datang menyambut kedatanganmu, bukankah telah engkau peroleh beberapa pukulan mereka? Alhamdulillah, telah kusaksikan betapa engkau telah memperoleh apa yang engkau inginkan!”
Ibrahim menetap di kota Makkah.
Ia selalu ditemani beberapa orang sahabat dan ia memperoleh nafkah sebagai tukang kayu.










 Larry Tesler
Larry Tesler











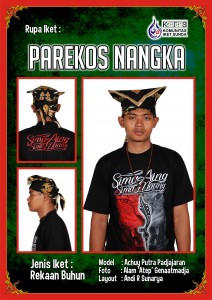










[…] Lihat Gambar Sumber @ http://www.infobdg.com […]
[…] Lihat Gambar Sumber @ http://www.infobdg.com […]